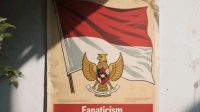Kecantikan dalam Bayang Ilusi
Sebagai perempuan yang pernah berkecimpung di dunia pageant, saya sering merenungkan bagaimana panggung gemerlap bisa memikat sekaligus menyesatkan. Pada 1995, saya pernah menjadi finalis ajang nasional, lalu menjabat sebagai National Director Indonesia untuk kontes kecantikan internasional periode 2023–2024. Dari pengalaman itu, saya belajar bahwa kecantikan tidak hanya soal fisik, tetapi juga perpaduan antara rasa percaya diri dan penerimaan diri.
Namun di era media sosial, kecantikan kian terjebak dalam “halu-halu” ilusi yang dibangun oleh filter, algoritma, dan endorsement. Hampir semua perempuan ingin tampil menarik dan diakui. Pertanyaannya: apakah ini dorongan alami dari naluri biologis, atau sekadar mesin kapitalisme yang mencetak standar?
Biologi, Budaya, dan Impian Cinderella
Secara biologis, hormon estrogen berperan dalam membentuk perilaku feminin: penuh empati, lembut, dan ingin terlihat menarik. Dorongan ini wajar dalam perspektif evolusi, karena penampilan sering dikaitkan dengan daya tarik dan keberlangsungan generasi.
Sejak kecil, banyak gadis tumbuh dengan kisah Cinderella atau boneka Barbie. Cerita dan mainan itu menanamkan keyakinan bahwa kecantikan adalah tiket menuju kebahagiaan.
Namun, survei Dove Global Beauty and Confidence (2023) menunjukkan lebih dari 80 persen perempuan di seluruh dunia merasa tertekan oleh standar kecantikan yang tidak realistis. Tekanan ini berujung pada ketidakpuasan terhadap tubuh sendiri, bahkan ketika mereka sebenarnya sehat dan normal.
Budaya membentuk imajinasi kecantikan sejak dini, lalu kapitalisme memperkuatnya menjadi industri raksasa.
Meledaknya Tren Operasi Plastik
Tekanan sosial terhadap standar fisik makin kuat dengan meledaknya tren operasi plastik (oplas). Laporan International Society of Aesthetic Plastic Surgery (ISAPS) 2024 mencatat lebih dari 17,4 juta prosedur bedah estetika dilakukan secara global, meningkat 10 persen dibanding tahun sebelumnya.
Di Indonesia, fenomena ini paling terasa di kalangan Gen Z dan milenial. Survei media pada 2023 menunjukkan kenaikan pasien muda di klinik kecantikan hingga 25 persen. Prosedur populer antara lain filler bibir, botox, dan rhinoplasty. Alasan dominan: meningkatkan rasa percaya diri.
Namun, ketika dilakukan berulang demi memenuhi ekspektasi publik, kebutuhan itu berubah menjadi obsesi. Normalisasi oplas bahkan kerap terlihat di kalangan selebriti dan sosialita. Tidak jarang warganet bergurau bahwa banyak figur publik memiliki wajah serupa karena ditangani dokter yang sama.
Korea Selatan masih menjadi pusat operasi estetika global dengan rasio 24,4 prosedur per 1.000 orang. Indonesia memang lebih kecil (0,569 per 1.000 orang), tetapi grafiknya meningkat tajam. Fenomena ini menegaskan bahwa oplas kini bukan sekadar pilihan pribadi, melainkan tren sosial yang ditopang industri.
Pageant dan Standar Baru
Fenomena estetika modern juga merambah panggung pageant. Di beberapa ajang internasional, peserta yang menjalani operasi tidak lagi dianggap tabu. Bahkan pernah ada kompetisi khusus seperti Miss Plastic Hungary 2009, di mana sponsor utamanya adalah klinik bedah plastik.
Contoh ekstrem datang dari Brasil: seorang runner-up Miss Bum-Bum hampir kehilangan nyawa akibat komplikasi implan bokong. Fakta ini menegaskan bahwa kecantikan dalam kontes tidak lagi sekadar refleksi kepribadian, tetapi kerap hasil intervensi medis yang mahal.
Saat saya mengikuti pageant pada 1995, karisma, intelektualitas, dan kepribadian masih mendapat porsi utama. Kini, tekanan tampil “sempurna” membuat banyak peserta rela menghabiskan ratusan juta rupiah demi memenuhi standar industri.
Biaya, Industri, dan Kapitalisme
Biaya operasi estetika di Jakarta sangat bervariasi: rhinoplasty rata-rata Rp20–35 juta, implan payudara Rp50–60 juta, sedangkan facelift atau body contouring bisa menembus Rp100 juta lebih. Beberapa klinik premium bahkan mematok tarif jauh di atas itu.
Jika tujuan hanya sekadar tampil “sempurna” di media sosial, bukankah lebih murah mengedit foto dengan aplikasi gratis? Namun, pola pikir konsumen sudah dibentuk oleh kapitalisme kecantikan.
Menurut Euromonitor International (2024), nilai pasar kosmetik Indonesia telah menembus Rp100 triliun, didominasi merek global. Iklan gencar menampilkan citra perempuan berkulit putih, langsing, dan berwajah simetris—standar yang tidak realistis, tetapi efektif mencetak konsumen loyal.
Jurnal Perempuan (2023) menyebut kapitalisme kecantikan menjerat perempuan dalam siklus konsumsi tanpa henti. Sama seperti tas bermerek ratusan juta yang diproduksi massal dengan biaya murah, konsumen membeli simbol status, bukan fungsi. Bedanya, kini “merek” itu melekat di wajah hasil operasi.
Dampak Psikologis: Dari Percaya Diri ke Obsesi
Alasan pro-oplas biasanya sederhana: menambah percaya diri. Namun penelitian di Neliti (2022) menunjukkan perempuan dewasa yang menjalani operasi estetika justru cenderung mengalami kecemasan tinggi terhadap citra tubuh. Kepuasan pascaoperasi sering bersifat sementara, lalu disusul keresahan baru.
Fenomena ini berkaitan dengan Body Dysmorphic Disorder (BDD), yaitu gangguan di mana seseorang terobsesi pada “cacat” imajiner hingga melakukan tindakan berulang. Alih-alih menyelesaikan masalah, industri kecantikan justru memperkuat lingkaran setan ini.
Risiko Sosial dan Moral
Operasi plastik dengan biaya sendiri tentu sah. Masalah muncul ketika gaya hidup glamor dibiayai dengan cara tidak etis: dari pinjaman ilegal, skandal korupsi, hingga hubungan transaksional. Tak jarang figur sosial yang tampak kinclong di Instagram akhirnya terseret kasus kriminal.
Kajian ekofeminisme (2024) mengingatkan bahwa kapitalisasi tubuh perempuan bukan hanya merampas sumber ekonomi tradisional, tetapi juga menjerat dalam konsumerisme patriarkal. Kecantikan diperlakukan layaknya komoditas bisa dibeli, dijual, dan dipamerkan tanpa mempertimbangkan kesehatan maupun martabat perempuan itu sendiri.
Kembali ke Rasionalitas dan Self-Love
Lantas, mengapa tidak tampil apa adanya? Pertanyaan ini sering muncul setiap kali saya bercermin menatap kerutan usia. Jawabannya sederhana namun sulit: tekanan sosial. Kita kerap mengukur kebahagiaan dari jumlah like dan komentar.
Pageant hanyalah salah satu panggung yang memperbesar persoalan. Branding “halu-halu” menjadikan mahkota seolah simbol kesempurnaan, padahal sering kali hanya cermin ketidakpuasan. Industri kapitalisme berhasil menggeser tolok ukur kecantikan dari pencapaian personal menjadi standar buatan mesin.
Namun setelah tepuk tangan berhenti, realitas kembali menyapa. Mahkota hanyalah permainan masa kecil, seperti boneka Barbie. Kebahagiaan sejati bukan datang dari wajah sempurna, melainkan penerimaan diri.
Sebagaimana yang saya pelajari di panggung maupun kehidupan: cantik itu karena menjadi diri sendiri, bukan karena “da dah manjah” versi kapitalisme. Mari gunakan rasionalitas, bukan sekadar ikut arus ilusi. Boleh saja mengedit foto, tetapi jangan lupa juga “mengedit jiwa”membangun self-love, karena itulah yang abadi.
Penutup
Kecantikan selalu menjadi sumber daya tarik, peluang, sekaligus jebakan. Dari biologi hingga kapitalisme, dari dongeng Cinderella hingga mahkota pageant, perempuan berhadapan dengan ekspektasi yang sering melelahkan.
Di tengah gemerlap industri, ada satu hal yang seharusnya tak tergantikan: penerimaan diri. Sebab pada akhirnya, kecantikan sejati bukanlah ilusi digital atau hasil pisau bedah, melainkan keberanian untuk tampil apa adanya.
Novita Sari Yahya
Kegiatan sehari-hari penulis dan peneliti.
Penulis buku
1. Romansa Cinta
2. Padusi: Alam Takambang Jadi Guru
3. Novita & Kebangsaan
4. Makna di setiap rasa antologi 100 puisi bersertifikat lomba nasional dan internasional
5. Siluet cinta, pelangi rindu
6. Self Love : Rumah Perlindungan Diri.
Kontak pembelian buku : 089520018812
Instagram: @novita.kebangsaan